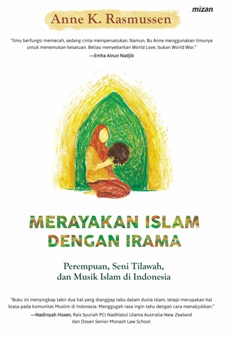
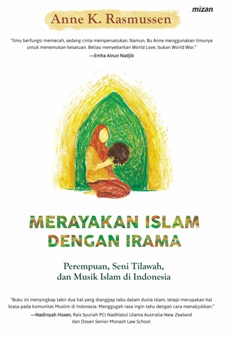
Merayakan Islam dengan Irama membawa pembaca ke jantung praktik seni tilawah dan musik religius di Indonesia, rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Anne K. Rasmussen mengeksplorasi kekayaan pemandangan suara di masyarakat, membaur di tempat berkembangnya pelafalan teks-teks suci Al-Qur'an yang ditampilkan oleh perempuan, dan mengamati keragaman gaya dan genre musik Islam yang dipengaruhi budaya Arab. Berdasarkan penelitian etnografi yang dimulai sejak akhir Orde Baru dan berlanjut ke era Reformasi, buku ini mempertimbangkan peran kuat musik dalam ekspresi perayaan akan keislaman dan yang terpenting, kaitannya dengan kebangsaan.
-
Ini adalah buku tentang praksis musik religius di Indonesia. Karya ini dimulai hampir secara tidak sengaja pada musim semi 1996. Sebelum berangkat ke Indonesia untuk bergabung dengan suami saya di Jakarta pada tahun itu, saya membeli Al-Quran berteks Arab yang disertai terjemahan bahasa Inggris-nya oleh Zafrulla Khan (1991) di sebuah toko buku di Dearborn, Michigan, tempat saya melakukan penelitian etnografi dengan komunitas Arab-Amerika. Saya juga membeli Kamus Indonesia-Inggris—yang banyak digunakan—karya John M. Echols dan Hassan Shadily edisi 1994. Saya tertarik menjajaki kemungkinan melakukan studi ilmiah tentang tradisi tilawah Al-Quran di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Buku Kristina Nelson The Art of Reciting the Quran (1986) merupakan sebuah karya panutan bagi saya, dan saya terpikir untuk membandingkan tradisi tilawah di Mesir—yang dia gambarkan dengan sangat indah—dengan tradisi tilawah di Indonesia. Meskipun perbandingan seperti itu rasanya di luar jangkauan saya; buku Nelson, terjemahan Al-Quran oleh Khan, dan kamus itu sering menemani perjalanan saya antara Indonesia dan Amerika Serikat—dan kemudian antara dua tempat tersebut dan Filipina. Buku-buku itu saya baca secara teratur.
Minat awal yang tumbuh pada musim semi 1996 itu berkembang serius pada 1999 ketika saya kembali ke Jakarta sebagai seorang sarjana Fulbright. Pada saat itu fokus saya adalah tradisi tilawah, dengan penekanan pada tilawah model langgam Mesir. Dalam perkembangannya, ada dua aspek utama yang saya soroti dari proyek tersebut. Pertama, keterlibatan perempuan dalam seni pertunjukan Islam di Indonesia. Kedua, nilai ritual dari berbagai pertunjukan musik Islam.
Ketertarikan saya pada musik Islam—baik berupa nyanyian kelompok maupun pertunjukan religius oleh sekelompok penyanyi, instrumentalis, dan penari yang terorganisasi—lebih dari sekadar soal kebolehan penggunaan musik dalam konteks tilawah. Pertunjukan musik Islam bahkan dianggap sebagai bagian integral dari acara ritual, sosial, dan kemasyarakatan yang melibatkan tilawah. Kenyataannya, para qari profesional yang saya kenal senang menyanyi dan melakukannya dalam konteks pertemuan ritual dan sosial. Selain itu, terkadang saya sendiri terlibat dalam pertunjukan musik ritual dan sosial jika diminta. Saya diminta tampil, baik sebagai solois, bernyanyi, dan bermain ‘ud (gitar khas Arab) maupun berkolaborasi dengan peserta lain, termasuk para qari/qariah profesional dan amatir. Oleh karena itu, hubungan saya—baik jangka pendek maupun jangka panjang—dengan para penasihat kegiatan riset ini sering difasilitasi oleh keterlibatan saya dalam musik Arab. Bahkan, dalam penelitian ini, pertunjukan musik merupakan salah satu wahana terbaik dalam pertukaran gagasan secara bermakna.
Pada tahap awal riset, saya mengira bahwa para qari/qariah itu hanya memungkinkan saya mengeksplorasi minat saya terhadap gaya tilawah mereka serta berbagai gaya dan genre seni musik Islam. Saya memang seorang ahli etnomusikologi dan bukan pakar Islam, Arab, atau Al-Quran—hal yang tentu mereka maklumi. Namun, ada satu peristiwa yang mengubah arah riset saya. Saya didorong oleh beberapa penasihat saya untuk pergi ke Kota Medan, tempat Yusnar Yusuf, seorang qari terkenal dan pegawai Kementerian Agama, tinggal. Yusnar meyakinkan saya bahwa saya akan merasakan lingkungan yang kaya dengan qari/qariah dan penyanyi musik Islam, beberapa di antaranya anggota inti dari IPQAH (Ikatan Persaudaraan Qari/Qariah Hafiz/Hafizah). Untuk melengkapi acara yang saya rancang bersama Yusnar Yusuf, dua ahli etnomusikologi dari Universitas Sumatra Utara, Rithaony Hutajulu dan Irwansyah Harahap, serta Ed Van Ness dari Medan International School dengan baik hati telah menyiapkan tiga materi presentasi bagi saya. Aktivitas saya dengan para rekan dan mahasiswa etnomusikologi akan—saya perkirakan—berjalan sesuai dengan rencana acara saya dengan para qari/qariah. Berdasarkan sejumlah kategori yang saya ketahui sebagai pengkaji budaya Timur Tengah dan Islam, saya yakin bahwa dua minat saya ini (tradisi pertunjukan keagamaan dan pertunjukan musik) tidak beririsan, meskipun bisa tumpang-tindih.
Acara pertama yang saya hadiri adalah sebuah haflah atau pagelaran tilawah Al-Quran. Suasananya sangat musikal ketika pria dan wanita berganti-ganti antara tilawah solo dan kasidah lagu-lagu Arab secara berkelompok. Estetika Arab tentang tarab—emosi dan interaksi musikal yang kuat—pada acara tersebut diperkuat oleh pemutaran kaset penyanyi Mesir Umm Kultsum. Sebuah “bonus” haflah—kali ini diadakan di Medan, di rumah Adnan Adlan 2 hari kemudian—menampilkan pertunjukan yang nyaris merupakan perpaduan antara tilawah dan musik, yang didahului makan prasmanan.1 Acara tersebut juga termasuk penampilan impromptu saya sendiri dan Nur Asiah Djamil, mantan juara qariah, penyanyi kasidah, dan pemimpin grup kasidah perempuan Nada Sahara, yang telah menghasilkan sejumlah rekaman terkenal.
Pada hari lain di pekan itu, rekan etnomusikolog saya dari Universitas Sumatera menyelenggarakan sebuah pertemuan dengan sekelompok musisi khusus gambus dan musik Melayu pimpinan Zulfan Effendi. Irwansyah dan Rithaony (Rita) menjemput saya dari hotel dengan mobil van mereka, yang sudah penuh muatannya oleh para musisi kelompok Zulfan Effendi dan instrumen mereka. Kami lalu berangkat ke rumah Irwansyah dan Rita, tempat sekelompok mahasiswa etnomusikologi mereka sudah menunggu kami. Sepanjang petang hingga larut malam, kami mendiskusikan musik, bertukar pertunjukan, dan bermain bersama. Ketika teman-teman qari saya—Yusnar Yusuf dan Gamal Abdul Naser Lubis—mendadak datang untuk sesi wawancara dan improvisasi kelompok, antusiasme mereka untuk “bermusik” begitu jelas (Small, 1998). Peristiwa ini dan banyak momen penting dalam riset saya makin menegaskan bahwa bagi banyak qari, peralihan yang halus dan teratur—dari tilawah ke bernyanyi hingga bermusik, lalu kembali ke tilawah—merupakan hal yang lazim, bukan perkecualian.
Meski spektrum sikap terhadap musik begitu luas—mulai dari yang membolehkan, memperingatkan, hingga melarang—dunia Islam kaya dengan genre musik dan seni pertunjukan, dari nyanyian religius hingga musik yang terkenal secara internasional seperti qawwali Pakistan atau repertoar musik dan tarian Tarekat Maulawiyah di Turki. Indonesia merupakan rumah besar bagi berbagai jenis musik islami yang luar biasa. Pengakuan dan keterlibatan aktif dalam musik Islam dari berbagai kalangan dan lapisan penduduk telah menempatkan Indonesia berada di kelas tersendiri di dunia Islam. Beragam musik Nusantara berasal dari beragam wilayah, yang secara geografis begitu luas dan tersebar. Perjalanan di antara sekitar enam ribu pulau berpenghuni sangatlah sulit. Dengan tiga ratus kelompok etnis yang tersebar di seluruh Nusantara dan dengan jumlah bahasa yang hampir sama banyaknya, keragaman seni pertunjukan di Indonesia sangatlah menakjubkan. Meski tradisi-tradisi daerah—beberapa di antaranya kini dilembagakan di sekolah-sekolah seni—berada di bawah pengaruh tradisi kerajaan yang otoriter, budaya kolonial, dan bentuk-bentuk modern yang diadopsi dari seluruh dunia, keragaman musik di Indonesia tetap tidak tertandingi.2 Keragaman kreatif ini meluas ke dunia seni musik Islam di negara ini.
Meskipun proses penyebaran Islam ke Indonesia bisa diperkirakan melibatkan proses pemaduan budaya Arab dengan keragaman budaya lokal di negara ini, hal ini nyaris tidak terjadi. Sebagian alasan mengapa ekspresi budaya-budaya lokal dari agama Islam ini begitu hidup dan terus berkembang adalah bahwa para saudagar Muslim yang kali pertama memperkenalkan keyakinan dan praktik Islam merupakan kelompok-kelompok multikultural yang membawa Islam yang “bervariasi” karena “keragaman asal-usulnya”.
“Pada tahap awal penyebaran Islam (ke wilayah Nusantara), arus perdagangan dari Yaman dan Pantai Swahili ke Pantai Malabar dan Teluk Benggala begitu kuat, sebagaimana hubungan erat dengan kaum Muslim di Tiongkok dan India. Para pedagang Muslim dari Tiongkok barat juga menetap di kota-kota di pesisir Tiongkok dan orang-orang Muslim Tiongkok mengembangkan hubungan penting dengan masyarakat di Vietnam tengah, Kalimantan, Filipina selatan, dan pantaiJawa. Sejumlah besar pedagang Muslim dari berbagai wilayah di India (misalnya Bengal, Gujarat, Malabar) berdatangan ke Asia Tenggara dan berperan juga sebagai penyebar agama Islam” (Andaya, 2007: 11).
Pada akhir abad ke-18 dan 19 ketika kontak dengan Arab Timur Tengah meningkat melalui orang-orang Nusantara yang melakukan perjalanan terutama ke Saudi Arabia dan Mesir untuk belajar agama dan berhaji dan pada abad ke-20 ketika alat rekam fonogram dan siaran radio membawa suara musik dan ritual dari dunia Arab ke Nusantara, beragam sumber otoritas Islam—yang menurut Andaya awalnya bersifat multikultural—mulai mengalami proses penyeragaman. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, ekspresi seni berbahasa Arab dari dunia Arab Timur—khususnya tilawah Al-Quran, azan, lagu-lagu religius, bahkan seni dan musik populer yang melibatkan penyanyi dan instrumentalis—menjadi dominan.
Pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa kekuatan dan prestise serta bahasa wacana kaum inteligensia telah berlangsung sepanjang masa. Selama periode awal penyebaran Islam ke Nusantara, bahasa Arab menarik bagi kelas penguasa Indonesia karena ini merupakan bahasa kaum terpelajar. Pada pergantian abad ke-21, bahasa Arab—sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa Islam—terus menjadi media bagi dakwah Islam. Terkait dengan ini, pakar Islam dan perbandingan agama, Mahmoud Ayoub, mengakui bahwa seni tilawah Al-Quran sama pentingnya dengan ilmu tafsir Al-Quran dalam tradisi kaum Muslim.
“Secara tradisional, umat Islam mendekati Al-Quran dari dua sudut pandang yang berbeda tetapi berkaitan, yakni tafsir Al-Quran dan tilawah Al-Quran. Pada tafsir, mereka mendedikasikan pikiran terbaik mereka; pada tilawah, mereka mendedikasikan suara dan talenta musikal terbaik mereka. Ilmu tafsir bertujuan menyingkap makna teks suci sementara seni tilawah menjadi kendaraan utama dalam dakwahnya” (Ayoub, 1993: 69).
Suara dari teks Arab Al-Quran itu sendiri merupakan sumber kekuatan dan pesona yang berasal dari Ilahi dan itu hanya bisa diaktifkan oleh qari/qariah yang terlatih.
Kaum perempuan yang hidup dari tradisi tilawah inilah yang menjadi inti riset saya. Kepada merekalah saya menyampaikan terima kasih yang terdalam. Maria Ulfah dan komunitas murid, guru, dan para stafnya di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), sebuah perguruan tinggi perempuan untuk studi Al-Quran, mengundang saya untuk berbagi dunia mereka dan mengajarkan cara-cara baru untuk melakukan riset di komunitas yang utamanya perempuan. Maria Ulfah—mulanya seorang guru dan informan, kemudian menjadi seorang penasihat dan kolaborator, dan akhirnya seorang mentor dan teman—membantu saya merasakan, banyak di antaranya terlalu halus untuk ditulis di sini, bagaimana rasanya menjadi seorang perempuan Muslim, seorang Jawa, seniman, bintang, humanis, dan profesional perempuan yang bekerja di dalam struktur patriarki yang mapan. Seiring dengan pergeseran fokus dari tilawah Al-Quran ke karya perempuan dalam tradisi Islam, Maria semakin tertarik untuk membagikan ceritanya, perspektifnya, dan pengetahuannya tentang Islam “perempuanis” (bukan feminis) kepada dunia luar, sebuah keinginan yang terus saya dorong untuk dia lakukan secara konsisten. Kini dia sering diminta mempresentasikan ceramah internasional tentang peran perempuan dalam Islam, dan pada riwayat hidupnya kini dia memasukkan gender sebagai bidang keahliannya.
3 Saya berharap kolaborasi kami mendorong perkembangan kariernya, sebagaimana hal ini telah meningkatkan karier saya. Kehadiran Maria yang dinamis, otoritatif, dan murah hati berada di balik keseluruhan karya etnografis ini. Dan, meskipun saya bangga menampilkan dia, saya sepenuhnya menyadari keterbatasan kemampuan saya untuk mengomunikasikan kekayaan sejarah dan kompleksitas kontemporer dari dunianya.