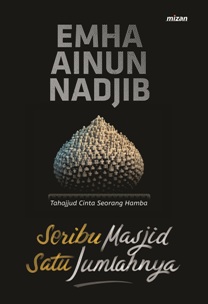
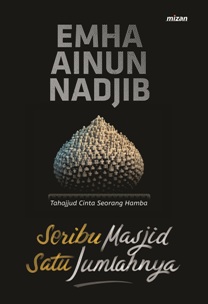
Bahkan seribu masjid, sejuta masjid
Niscaya hanya satu belaka jumlahnya
Sebab tujuh samudra gerakan sejarah
Bergetar dalam satu ukhuwwah Islamiyyah
Dalam buku ini, pembaca akan mendapati ungkapan cinta seorang manusia kepada sesamanya dan Penciptanya. Meskipun tetap dengan nada yang kadang menusuk tajam—karena sarat kritik atas kehidupan sosial kita yang pincang—kelima puluh proisi yang tampil di sini mencuatkan kepekaan dan kedalaman pemikiran seorang seniman dalam menangkap ayat-ayat Tuhan.
Assalamu‘alaikum
Di penghujung 1989, saya berusaha “mencuri” kesempatan untuk menghimpun puisi-puisi yang selama beberapa tahun ini pada umumnya hanya saya publikasikan secara lisan, yakni membacakannya di berbagai forum dan kalangan masyarakat—di berbagai kota, daerah, pulau—rata-rata tiga kali sebulan.
Pengumpulan yang saya lakukan berdasarkan jenis nuansa, wilayah tema, konteks, serta proyeksi terhadap “segmen pasar” pendengar atau pembaca.
Ada kumpulan puisi sosial yang biasanya untuk para mahasiswa. Ada kumpulan puisi cinta buat peristiwa-peristiwa khusus. Ada puisi yang—katakanlah—eksklusif individual, yang nuansanya amat pribadi tapi ternyata memuat juga refleksi-refleksi sosial.
Dan Seribu Masjid, Satu Jumlahnya adalah puisi-puisi yang selama ini saya pergaulkan dengan berbagai jamaah kaum Muslim di berbagai tempat. Pola ungkap dan idiom-idiom yang saya gunakan, bahkan keseluruhan substansi dan bentukannya saya usahakan orientatif dan kontekstual terhadap alam kehidupan mereka.
Kemudian di samping kumpulan Lautan Jilbab yang telah terbit pada 1989 ini, yang belum berhasil saya selesaikan sejak 1984 adalah Syair Al-Asma’ Al-Husna’. Sangat berat menuliskannya.
Sebagian dari puisi-puisi Seribu Masjid, Satu Jumlahnya ini, merupakan hasil revisi final dari beberapa puisi yang—di samping saya publikasikan secara lisan—pernah termuat dalam semacam penerbitan darurat dan lepas untuk kepentingan acara tertentu.
Beribu syukur kepada Allah, pemilik segala ilmu dan satu-satunya pelontar ilham. Terima kasih berat kepada semua ikhwan dan akhwat, kepada seluruh alam dan malaikat, atas kemesraan kerja sama dalam usaha mengkhalifahi kehendak-kehendak Allah.
Wassalam
Emha Ainun Nadjib
Seribu Masjid
Satu Jumlahnya
Satu
Masjid itu dua macamnya
Satu ruh, lainnya badan
Satu di atas tanah berdiri
Lainnya bersemayam di hati
Tak boleh hilang salah satunya
Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu
Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu
Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu
Dua
Masjid selalu dua macamnya
Satu terbuat dari bata dan logam
Lainnya tak terperi
Karena sejati
Tiga
Masjid batu bata
Berdiri di mana-mana
Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya
Timbul tenggelam antara ada dan tiada
Mungkin di hati kita
Di dalam jiwa, di pusat sukma
Membisikkan nama Allah Ta‘ala
Kita diajari mengenali-Nya
Di dalam masjid batu bata
Kita melangkah, kemudian bersujud
Perlahan-lahan memasuki masjid sunyi jiwa
Beriktikaf, di jagat tanpa bentuk tanpa warna
Tubuh kita bertakbir
Ruh mengagumi-Nya tanpa suara
Ruh bersembahyang tanpa gerak
Menjerit dengan mulut sunyi
Empat
Sangat mahal biaya masjid badan
Padahal temboknya berlumut karena hujan
Adapun masjid ruh kita beli dengan ketakjuban
Tak bisa lapuk karena asma-Nya kita dzikir-kan
Masjid badan gampang binasa
Matahari mengelupas warnanya
Ketika datang badai, beterbangan gentingnya
Oleh gempa bumi ambruk dindingnya
Masjid ruh mengabadi
Pisau tak sanggup menikamnya
Senapan tak bisa membidiknya
Politik tak mampu memenjarakannya
Negeri Kaum Beribadah
Di tengah pengembaraan, tibalah aku di sebuah negeri kaum beribadah, namun betapa susah untuk menemukan masjid.
Sepanjang siang aku menyelinapi kampung-kampung tanpa menjumpainya, dan jika malam turun termangulah aku di bawah bintang-bintang.
Di manakah masjid? Ketika malam berangkat makin jauh memasuki relung sunyi dan cintanya, kembali aku bersandar di pangkal semesta.
Kemudian tatkala fajar pun merekah, telah berada kembali aku di dunia kecil yang selalu riuh rendah ini sambil tetap bertanya—di mana masjid?
Siang membakar, aku terduduk lesu di bawah sebatang pohon, hampir tertidur oleh kebuntuan—ketika seorang tua renta berwajah kumuh menghampiriku.
“Di mana masjid?”—tergagap aku bertanya, dijawab langsung olehnya dengan pertanyaan yang ruwet, “Kenapa engkau bertanya tentang masjid dengan bertanya tentang masjid?”
Tentulah aku ini sedang berhadapan dengan seseorang yang bingung hidupnya, “Aku bertanya tentang masjid”— kataku—“Bukankah pertanyaanku amat sederhana?”
Dia tertawa. “Bersujudlah, maka engkau telah mendirikan masjid. Bukankah jawabanku tak kalah sederhana?”
Kesal aku dibuatnya. “Aku bertanya di mana masjid seperti aku bertanya di mana pasar, di mana gedung pemerintah, di mana sungai atau kamar kecil!”—suaraku mengeras.
Orang sinting ini pun tertawa riuh, “Alangkah pendek pengembaraanmu! Masjid ialah tempat bersujud. Dan yang namanya tempat itu tidak harus ruang, bangunan, bentuk, dinding, tiang, atau hiasan-hiasan. Ia bisa saja sebuah perbuatan, sekecil apa pun. Setiap perbuatan untuk Allah adalah masjid bagi nilai hidupmu ....”
Aku hendak memotongnya karena aku ini tergolong orang yang kurang bisa menghormati siapa pun saja yang berpikiran terlalu mewah. Tapi, kata-kata lelaki gila itu terus mengguyur bagai hujan—
“Manusia tak punya hak untuk bertanya tentang masjid, karena dia tak punya kemampuan untuk melihat masjid, kecuali yang bersemayam di dalam dirinya sendiri, karena memang tak ada orang lain yang sanggup melihat apakah seseorang sungguh-sungguh menyembah Allah atau tidak. Kalau engkau menyaksikan beribu-ribu orang mensujudkan badannya di bangunan besar berkubah yang disebut masjid, bisa tahukah engkau apakah jiwa mereka sungguh-sungguh bersujud? ....”
Kubiarkan dia menyelesaikan guyuran hujannya, “Masjid itu bukan di mana atau tak di mana. Bukan ada atau tak ada. Melainkan terjadi ataukah tak terjadi. Kalau engkau bersujud, dalam sembahyang maupun dalam setiap pekerjaanmu, maka terjadilah ia. Adapun bangunan, itu tinggal benda ....”
Kali ini aku terpaksa memotongnya. Aku katakan kepadanya bahwa derajatku terlampau rendah untuk diajak berbicara oleh seorang—yang barangkali—Sufi seperti dia.
Dia malah tertawa keras bagai seorang pemabuk, “Aku bukan sufi!”—katanya—“Sufi itu omong kosong. Kuminta kau jangan ganggu aku dengan merek dagang apa pun. Aku tak bernama. Aku sudah tak bernama. Aku tak ada. Kau jangan gila. Bagaimana mungkin aku ada. Aku tak punya kemungkinan untuk mengada. Aku tak punya kesanggupan untuk ada. Aku hanya diadakan. Oleh karena itu, sesungguhnya tak ada ....”
1988